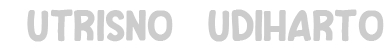Opini TEMPO, 7 Mei 2016
Dari Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
Sajak-sajak Mustofa Bisri tak pernah dibangun dari statemen yang marah. Puisi itu bahkan bisa kocak. Lebih sering bait-baitnya gundah -- kegundahan yang menarik: seorang alim melihat keadaan rumpang di sekitarnya tanpa ia merasa jadi lebih suci dari sekitarnya itu. Tiap kali sajak penyair dan kiyai dari Rembang ini mengandung kritik sosial, tiap kali ia serasa ditikamkan ke satu bagian hidupnya sendiri.
"Tuhan semakin banyak" mengemukakan satu paradoks zaman ini: makin sering Tuhan dipajang di pelbagai laku dan kata-kata, makin jauh Ia dari bumi. "Aku" manusia telah menggantikan-Nya:
Di mana-mana tuhan, ya Tuhan
Di sini pun semua serba tuhan
Di sini pun tuhan merajalela
Memenuhi desa dan kota
Mesjid dan gereja
Kuil dan pura
Menggagahi mimbar dan seminar
Kantor dan sanggar
Dewan dan pasar
Mendominasi lalu lintas
Orpol dan ormas
Swasta dan dinas
Tuhan pun jadi "tuhan" (dengan "t"): bukan saja hanya jadi salah satu dari wujud di dataran benda-benda, tapi juga hanya sebuah bunyi yang diulang-ulang. Tuhan jadi banal. Iman jadi otomatik. Bersamaan dengan itu, "Aku" manusia menggantikannya dalam posisi di depan.
Khutbahku khutbah tuhan!
Fatwaku fatwa tuhan!
Lembagaku lembaga tuhan
Jama’ahku jamaah tuhan!
Keluargaku keluarga tuhan!
Puisiku puisi tuhan!
Kritikanku kritikan tuhan!
Darahku darah tuhan!
Akuku aku tuhan
Tentu saja ada perbedaan yang radikal antara "Akuku aku Tuhan" di akhir sajak itu dengan ekspresi mistik manunggaling kawulo gusti. Pengalaman seorang sufi adalah pertalian cinta; sajak Mustofa Bisri menunjukkan sebaliknya: Tuhan dipasang sebagai alat, mirip stempel. Dan puisi ini mencatatnya dengan masygul.
Tuhan yang "semakin banyak" yang disebut Mustofa Bisri agaknya seperti dewa-dewa Yunani dalam Illiad: mereka ikut intervensi dan bertikai dalam hampir tiap babakan Perang Troya. Atau mungkin yang terjadi sebaliknya: dalam perang yang bengis itu, para pelakunya ingin memindahkan tanggungjawab dan kesalahan kepada kekuatan di luar diri mereka -- kekuatan yang digambarkan sebagai mutlak dan bebas dan bisa berbuat tak semena-mena. Dan itulah dewa-dewa mitologi Yunani.
Roberto Calasso, yang beberapa novelnya adalah tafsir baru atas mitologi, menulis dalam La letteratura e gli dèi ("Sastra dan Para Dewa") bahwa sastra dapat merupakan siasat halus untuk membawa dewa-dewa lepas dari tempat mereka yang aman, bersih, dan kekal -- dari "klinik universal" (clinica universale) mereka. Sastra "mengembalikan mereka ke dunia, untuk diserakkan ke permukaan bumi, tempat mereka biasanya berdiam."
Dengan kata lain, sastra, karena tak meletakkan diri sebagai Kitab Suci, bisa membuat yang sakral jadi bagian hidup sehari-hari, bersentuhan dengan segala macam hal, termasuk yang terbuang, najis, dan kurang patut. Tapi biarpun terserak di seantero muka bumi, yang suci tetap tak jadi profan dan banal, selama ia tak dijadikan alat manusia seperti "tuhan" dalam sajak Mustofa Bisri.
Ada sebuah petuah agar kita membuat iman ibarat garam: sesuatu yang tak nampak namun meresap memberi corak, membubuhkan rasa tanpa berlebihan dan sebab itu tak membuat berat atau heboh dalam perjalanan.
Novel Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara, adalah contoh yang baik bagaimana iman selamanya hadir tak kurang dan tak berlebihan -- dan sebab itu tak berbenturan dengan kehidupan, bahkan ketika kehidupan berpindah dan berubah.
Novel ini sebuah rekaman rite of passage Ali Fikri, seorang anak muda Sumatra Barat. Ia selalu murid yang pintar sejak di madrasah tsanawiyah di Kabupaten Agam sampai dengan ketika ia belajar di Pondok Gontor, di Jawa Timur. Ia sebenarnya ingin masuk SMA, tapi pesan Amaknya yang ia cintai menahannya untuk tetap berada di jalur pendidikan agama. Sesekali ada kebimbangan, tapi Ali Fikri menyukai kehidupan di pesantren itu -- yang sebenarnya tak terpisah dari Indonesia yang 'modern'. Di sana ia juga bertemu dengan fragmen-fragmen dunia lain. Ia tak gentar mengalami beda dalam dirinya. Pesan Kiai Rais selalu dikenangnya: "Jangan berharap dunia yang berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah."
Maka dalam novel ini tak terasa ada guncangan dan krisis, ketika kesalihan kota kecil Indonesia bertaut dengan modernitas "Barat". Awal cerita di dekat Gedung Capitol yang diselimuti salju di Washington DC; akhir cerita: di bawah monumen Nelson di Trafalgar Square, London. Negeri Lima Menara dibuka dengan kata-kata Imam Syafi'i di abad ke-8 yang diajarkan kepada para murid Pondok Gontor: "Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih..."
Yang dirayakan gerak dan perjalanan. Tuhan sudah dengan sendirinya menyertai, tanpa, dalam kata-kata Mustofa Bisri, "mendominasi lalu lintas."
Dari Catatan Pinggir, TEMPO, 7 Mei 2016
Dari Catatan Pinggir Goenawan Mohamad
Sajak-sajak Mustofa Bisri tak pernah dibangun dari statemen yang marah. Puisi itu bahkan bisa kocak. Lebih sering bait-baitnya gundah -- kegundahan yang menarik: seorang alim melihat keadaan rumpang di sekitarnya tanpa ia merasa jadi lebih suci dari sekitarnya itu. Tiap kali sajak penyair dan kiyai dari Rembang ini mengandung kritik sosial, tiap kali ia serasa ditikamkan ke satu bagian hidupnya sendiri.
"Tuhan semakin banyak" mengemukakan satu paradoks zaman ini: makin sering Tuhan dipajang di pelbagai laku dan kata-kata, makin jauh Ia dari bumi. "Aku" manusia telah menggantikan-Nya:
Di mana-mana tuhan, ya Tuhan
Di sini pun semua serba tuhan
Di sini pun tuhan merajalela
Memenuhi desa dan kota
Mesjid dan gereja
Kuil dan pura
Menggagahi mimbar dan seminar
Kantor dan sanggar
Dewan dan pasar
Mendominasi lalu lintas
Orpol dan ormas
Swasta dan dinas
Tuhan pun jadi "tuhan" (dengan "t"): bukan saja hanya jadi salah satu dari wujud di dataran benda-benda, tapi juga hanya sebuah bunyi yang diulang-ulang. Tuhan jadi banal. Iman jadi otomatik. Bersamaan dengan itu, "Aku" manusia menggantikannya dalam posisi di depan.
Khutbahku khutbah tuhan!
Fatwaku fatwa tuhan!
Lembagaku lembaga tuhan
Jama’ahku jamaah tuhan!
Keluargaku keluarga tuhan!
Puisiku puisi tuhan!
Kritikanku kritikan tuhan!
Darahku darah tuhan!
Akuku aku tuhan
Tentu saja ada perbedaan yang radikal antara "Akuku aku Tuhan" di akhir sajak itu dengan ekspresi mistik manunggaling kawulo gusti. Pengalaman seorang sufi adalah pertalian cinta; sajak Mustofa Bisri menunjukkan sebaliknya: Tuhan dipasang sebagai alat, mirip stempel. Dan puisi ini mencatatnya dengan masygul.
Tuhan yang "semakin banyak" yang disebut Mustofa Bisri agaknya seperti dewa-dewa Yunani dalam Illiad: mereka ikut intervensi dan bertikai dalam hampir tiap babakan Perang Troya. Atau mungkin yang terjadi sebaliknya: dalam perang yang bengis itu, para pelakunya ingin memindahkan tanggungjawab dan kesalahan kepada kekuatan di luar diri mereka -- kekuatan yang digambarkan sebagai mutlak dan bebas dan bisa berbuat tak semena-mena. Dan itulah dewa-dewa mitologi Yunani.
Roberto Calasso, yang beberapa novelnya adalah tafsir baru atas mitologi, menulis dalam La letteratura e gli dèi ("Sastra dan Para Dewa") bahwa sastra dapat merupakan siasat halus untuk membawa dewa-dewa lepas dari tempat mereka yang aman, bersih, dan kekal -- dari "klinik universal" (clinica universale) mereka. Sastra "mengembalikan mereka ke dunia, untuk diserakkan ke permukaan bumi, tempat mereka biasanya berdiam."
Dengan kata lain, sastra, karena tak meletakkan diri sebagai Kitab Suci, bisa membuat yang sakral jadi bagian hidup sehari-hari, bersentuhan dengan segala macam hal, termasuk yang terbuang, najis, dan kurang patut. Tapi biarpun terserak di seantero muka bumi, yang suci tetap tak jadi profan dan banal, selama ia tak dijadikan alat manusia seperti "tuhan" dalam sajak Mustofa Bisri.
Ada sebuah petuah agar kita membuat iman ibarat garam: sesuatu yang tak nampak namun meresap memberi corak, membubuhkan rasa tanpa berlebihan dan sebab itu tak membuat berat atau heboh dalam perjalanan.
Novel Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara, adalah contoh yang baik bagaimana iman selamanya hadir tak kurang dan tak berlebihan -- dan sebab itu tak berbenturan dengan kehidupan, bahkan ketika kehidupan berpindah dan berubah.
Novel ini sebuah rekaman rite of passage Ali Fikri, seorang anak muda Sumatra Barat. Ia selalu murid yang pintar sejak di madrasah tsanawiyah di Kabupaten Agam sampai dengan ketika ia belajar di Pondok Gontor, di Jawa Timur. Ia sebenarnya ingin masuk SMA, tapi pesan Amaknya yang ia cintai menahannya untuk tetap berada di jalur pendidikan agama. Sesekali ada kebimbangan, tapi Ali Fikri menyukai kehidupan di pesantren itu -- yang sebenarnya tak terpisah dari Indonesia yang 'modern'. Di sana ia juga bertemu dengan fragmen-fragmen dunia lain. Ia tak gentar mengalami beda dalam dirinya. Pesan Kiai Rais selalu dikenangnya: "Jangan berharap dunia yang berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah."
Maka dalam novel ini tak terasa ada guncangan dan krisis, ketika kesalihan kota kecil Indonesia bertaut dengan modernitas "Barat". Awal cerita di dekat Gedung Capitol yang diselimuti salju di Washington DC; akhir cerita: di bawah monumen Nelson di Trafalgar Square, London. Negeri Lima Menara dibuka dengan kata-kata Imam Syafi'i di abad ke-8 yang diajarkan kepada para murid Pondok Gontor: "Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih..."
Yang dirayakan gerak dan perjalanan. Tuhan sudah dengan sendirinya menyertai, tanpa, dalam kata-kata Mustofa Bisri, "mendominasi lalu lintas."
Dari Catatan Pinggir, TEMPO, 7 Mei 2016